Puisi Esai oleh L. K. Ara
Di lereng bukit yang ditumbuhi kopi dan kenangan,
seorang pemuda meniup suling bambu
dengan irama yang tak sekadar mengisi udara—
tapi menyulam langit dan tanah,
antara hening dan harap,
antara sunyi dan suara.
Suara itu bukan sekadar bunyi,
ia adalah isyarat purba dari tubuh pegunungan,
yang turun dari leluhur kepada anak cucu
sebagai warisan yang tak tertulis
namun hidup di udara dan dada-dada yang tekun menjaga.
Ia meniup suling seperti memanggil roh air,
seperti berbincang dengan pohon-pohon damar,
dan sesekali seperti mengadu
tentang nasib orang-orang kecil
yang suaranya tak pernah sampai ke kota.
Dialah muazin tanpa mimbar,
tanpa menara,
tapi azannya mampu menggugah
mata batin dan mata sejarah.
“Suling ini bukan hiburan,” katanya,
“ini warisan suara kampung.
Ini panggilan agar kita tak hanyut
jadi manusia yang lupa daratan.”
Ia tumbuh dalam sunyi,
di rumah yang berdinding papan,
di kampung yang listriknya lebih sering mati
daripada nyala,
namun suara sulingnya tak pernah padam.
Dari lubang-lubang bambu yang kecil itu,
ia tiupkan doa para petani,
yang tanamannya dilanda kemarau panjang.
Ia tiupkan keluh kesah para janda,
yang ditinggal suami karena konflik atau merantau.
Ia tiupkan cerita anak-anak,
yang belum tahu apakah mereka masih punya tanah warisan,
atau hanya warisan luka.
Suaranya melintasi jalan setapak,
menyusup ke dalam dapur-dapur
dan menyapa nenek-nenek yang tengah menampi beras
dengan tubuh yang dulu gagah
saat menanam lada bersama suaminya
yang kini hanya nama di batu nisan.
“Di kota, muazin memanggil untuk salat.
Di sini, muazin kami meniup suling
agar semangat adat tidak mati,
agar roh gunung tetap mendengar
derita anak cucu mereka.”
Tiap senar nada yang ditiupkan
adalah tangga menuju ingatan.
Ia tiup dalam ritme Selawat Kenang,
ia mainkan dalam laras Linge Raya,
hingga satu desa berhenti sejenak dari kerjanya,
dan mendengarkan—
seperti mendengar perintah lembut
dari kakek buyut yang datang dalam suara angin.
Kadang ia meniup dengan mata tertutup,
seolah sedang berbicara
dengan makhluk tak kasat mata—
seorang datok yang pernah menyimpan naskah hikayat,
seorang guru yang mengajar huruf Arab Melayu
dengan kapur dan papan kayu.
Kadang ia menangis tanpa suara,
ketika sulingnya mengalunkan kisah
tentang sahabatnya yang tak pulang
karena pergi ke kota mencari kerja
dan kembali dalam berita duka.
Ia meniup dalam sunyi,
tapi yang mendengar adalah ratusan tahun.
Ia meniup dari lereng gunung,
tapi gema suaranya menjalar
sampai ke hati anak-anak muda
yang nyaris lupa apa itu Gayo.
Mereka yang kini lebih kenal tren TikTok
daripada irama suling nenek moyang.
Namun malam itu—
di tengah panggung kecil yang dibangun dari niat,
dan sinar lampu seadanya,
ia meniup suling di depan hadirin:
pejabat yang baru kenal Gayo,
penonton dari kota,
dan budayawan yang meneteskan air mata diam-diam.
“Lestarikan bukan hanya lewat museum,”
katanya seusai meniup,
“tapi lewat napas dan tangan.
Lewat darah yang percaya
bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri.”
Maka teruslah ia tiupkan sulingnya
di pagi yang berkabut dan malam yang senyap.
Sebab ia tahu,
sebuah bangsa yang lupa suara sulingnya
akan kehilangan cara menangis,
dan sebuah negeri yang kehilangan muazin seperti dia,
akan kehilangan cara bersyukur.
⸻
📌 Catatan:
Puisi ini adalah penghormatan kepada para penjaga seni dan suara di dataran tinggi Gayo, yang dalam keterbatasan tetap meniupkan napas budaya untuk generasi kini dan nanti. Suling bukan hanya instrumen—ia adalah pengingat bahwa di balik pegunungan yang sejuk, tersimpan kisah yang masih hangat dan hidup.



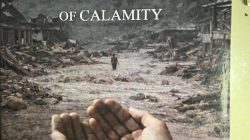


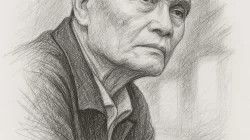






Respon (13)
Komentar ditutup.