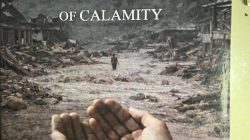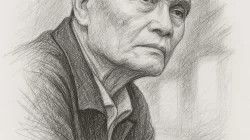LK Ara
Puisi Esai
Jakarta, 1987,
bagi saya, Maskirbi, dan Rosni Idham,
adalah sebuah jarak yang tak hanya soal kilometer,
tetapi soal mimpi yang harus dibayar dengan keberanian.
Dewan Kesenian Jakarta mengundang kami
ke Forum Puisi Indonesia ’87
di Taman Ismail Marzuki,
tapi ongkos kami tanggung sendiri.
Undangan, iya.
Transportasi? Silakan cari sendiri.
Kami tak menyerah.
Bupati Pidie, Nurdin AR,
yang setahun sebelumnya
menyelenggarakan Pertemuan Sastrawan ASEAN
di Universitas Jabal Ghafur,
menerima kami dengan senyum dan janji.
Ia teringat bagaimana kami hadir di Pidie,
bersama Mochtar Lubis,
Hamsad Rangkuti,
Taufiq Ismail, L K Ara,
dan Siti Zainon Ismail dari Malaysia.
Ia sediakan dua tiket,
dan Maskirbi dengan lapang hati berkata:
“Kalian saja yang berangkat.
Aku kembali ke Banda Aceh.”
Saya dan Rosni pun naik bus ke Medan,
dan untuk pertama kalinya
duduk di kursi pesawat Pelita Air Service,
menuju ibu kota
yang selama ini hanya terdengar namanya
dalam berita,
dalam puisi,
dalam angan-angan.
Di Forum Puisi Indonesia ’87 itu,
saya berdiri bersama para penyair dari seluruh tanah air:
Isbedi Stiawan ZS,
Acep Zamzam Noor,
Fakhrunnas MA Jabbar,
R Mulia Nasution,
dan begitu banyak nama
yang selama ini hanya saya kenal dari majalah sastra.
Di panggung, saya bacakan puisi “Nurlapan”
dengan gaya berdidong,
dan, entah dari mana datangnya keberanian,
saya buka baju di hadapan hadirin.
Bukan sekadar aksi,
tetapi penanda,
bahwa saya hadir,
bahwa puisi dari Meulaboh
juga punya tempat
di panggung nasional.
Malam-malam di Jakarta itu,
lampu-lampu TIM
memantulkan bayang saya sendiri:
seorang anak kampung,
penyair dari ujung barat Sumatra,
mencoba menulis namanya
di buku sejarah puisi Indonesia.
Dan mungkin,
di sanalah saya belajar,
bahwa puisi bukan hanya soal kata-kata,
tetapi soal keberanian:
menyeberangi jarak,
menyebrangi batas,
dan berdiri,
di bawah sorot lampu,
dengan dada terbuka.
⸻
📌 Catatan Kaki:
1️⃣ Forum Puisi Indonesia ’87 → forum nasional yang mempertemukan penyair dari seluruh Indonesia, diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta.
2️⃣ Berdidong → tradisi syair lisan masyarakat Gayo, Aceh, biasanya dinyanyikan dalam kelompok sambil berbalas pantun.
3️⃣ Pelita Air Service → maskapai penerbangan milik Pertamina, salah satu maskapai domestik aktif di era 1980-an.
4️⃣ TIM (Taman Ismail Marzuki) → pusat seni dan budaya legendaris di Jakarta, panggung utama bagi seniman Indonesia.
⸻
🌑 Metafora Kunci:
• “Jarak bukan hanya kilometer, tetapi mimpi yang harus dibayar keberanian” → mimpi besar selalu menuntut pengorbanan.
• “Lampu-lampu TIM memantulkan bayang saya sendiri” → melihat refleksi diri di panggung nasional, menemukan identitas.
• “Puisi bukan hanya soal kata-kata, tetapi keberanian” → seni adalah keberanian melampaui batas pribadi, bukan hanya karya.