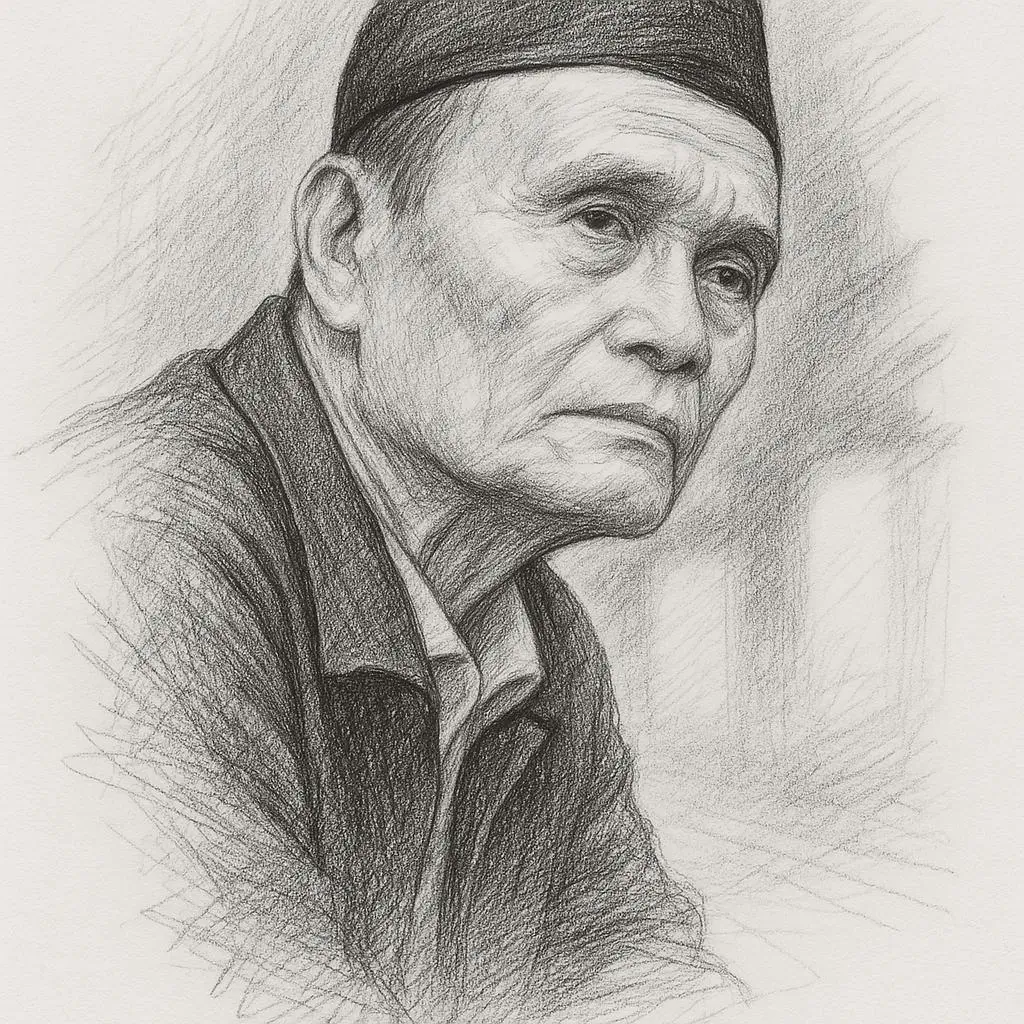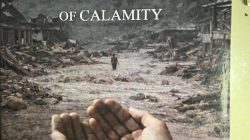KenNews.id – Setiap bencana meninggalkan lebih dari sekadar reruntuhan rumah dan lumpur di halaman. Ia juga merobohkan ketenangan batin, merobek rasa aman, dan membuat kata esok terasa rapuh. Dalam situasi seperti itu, sering muncul pertanyaan: apakah puisi—yang hanya rangkaian kata—mampu menghibur mereka yang sedang berduka?
Puisi tentu tidak dapat menggantikan makanan, selimut, atau obat-obatan. Ia tidak menghentikan hujan, tidak menahan longsor, dan tidak mengembalikan yang hilang. Namun puisi memiliki wilayah kerja yang berbeda: ia bekerja di ruang batin, tempat luka sering kali lebih dalam daripada yang tampak di permukaan.
Bagi korban bencana, penderitaan sering kali terasa sunyi. Tangis yang tertahan, ketakutan yang tak sempat diucapkan, dan kehilangan yang tak tahu harus diceritakan kepada siapa. Di sinilah puisi menemukan fungsinya—bukan sebagai hiburan yang riuh, melainkan sebagai pengakuan. Puisi berkata: engkau tidak sendirian; apa yang kau rasakan sah untuk dirasakan.
Puisi musibah yang baik tidak memamerkan air mata, tidak mengeksploitasi luka, dan tidak berdiri lebih tinggi dari penderitaan yang ia ceritakan. Ia menunduk. Ia memilih kata-kata yang jujur, sederhana, dan bersedia diam di antara baris-barisnya. Justru dalam kesenyapan itulah korban bencana sering menemukan ruang bernapas—ruang untuk merasa dipahami tanpa harus menjelaskan.
Dalam banyak kebudayaan, termasuk di Aceh dan Tanah Gayo, syair dan didong lahir dari peristiwa kolektif: perang, kelaparan, wabah, dan bencana alam. Syair tidak sekadar menghibur; ia menjadi cara masyarakat menyimpan ingatan dan merawat ketabahan. Ketika puisi dibacakan, yang hadir bukan hanya suara penyair, melainkan suara bersama—suara “kami” yang terluka namun masih berdiri.
Namun, puisi juga bisa gagal menghibur jika ia tergesa-gesa. Ketika luka masih basah, puisi yang terlalu indah justru terasa asing. Karena itu, puisi musibah memerlukan waktu, empati, dan kejujuran. Ia harus lahir dari keberpihakan pada manusia, bukan pada estetika semata.
Maka jawabannya bukan ya atau tidak secara mutlak. Puisi tidak menyembuhkan bencana, tetapi dapat menguatkan manusia yang mengalaminya. Ia tidak menutup duka, tetapi menemani duka agar tidak berubah menjadi keputusasaan. Dalam dunia yang sering sibuk memberi penjelasan, puisi memilih hadir sebagai pendengar.
Dan barangkali, bagi mereka yang kehilangan segalanya, satu hal yang paling dibutuhkan bukanlah nasihat panjang, melainkan keyakinan sederhana: bahwa penderitaan mereka dilihat, didengar, dan diingat. Di situlah puisi menemukan maknanya—sebagai pelukan yang terbuat dari kata-kata.