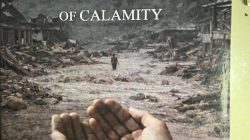Bencana tidak selalu datang sebagai kabar. Di Tanah Gayo, ia kerap tiba sebagai nyanyian. Didong—yang selama ini kita kenal sebagai seni hiburan, pergaulan, dan kebanggaan—sesungguhnya juga adalah arsip nurani. Ia menyimpan ingatan kolektif, menegur tanpa teriak, mengingatkan tanpa menunjuk wajah. Ketika alam terguncang, ceh didong sering kali lebih dahulu merasakannya, lalu mendendangkannya.
Dulu, pernah ada Ceh To’et. Dalam lagu “Redines”, ia mendendangkan longsor Redines jauh sebelum istilah mitigasi bencana dikenal luas di kampung-kampung Gayo. Liriknya tidak disusun sebagai laporan geologi, tetapi sebagai ratapan halus: tentang tanah yang kehilangan pegangan, tentang gunung yang tak lagi diam, tentang manusia yang lupa adab pada lereng. Lagu itu terdengar seperti kisah, padahal ia adalah peringatan.
Di situlah keistimewaan ceh didong. Mereka tidak menunggu papan pengumuman, tidak menanti konferensi pers. Mereka membaca tanda-tanda dari alam: hujan yang tak biasa, hutan yang menipis, suara tanah yang berubah. Semua itu diterjemahkan menjadi irama, menjadi bait, menjadi pengulangan yang pelan tapi menetap di ingatan. Didong menjadikan bencana bukan sekadar kejadian, melainkan pelajaran.
Pertanyaan “kapan ceh didong mendendangkan bencana?” sesungguhnya bisa dijawab: saat manusia mulai lupa. Lupa bahwa gunung bukan hanya sumber hasil, hutan bukan hanya angka, dan tanah bukan hanya objek. Ketika lupa itu menebal, ceh didong menyanyikannya sebagai cermin. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita kembali ingat.
Sayangnya, hari ini didong lebih sering dipanggil untuk pesta, lomba, dan panggung seremoni. Fungsinya sebagai penanda zaman mulai tersisih. Padahal, jika kita mau mendengar lebih dalam, didong masih mampu menjadi sistem peringatan dini yang paling jujur—karena ia lahir dari pengalaman hidup, bukan dari jarak kekuasaan.
Lagu “Redines” karya Ceh To’et adalah bukti bahwa seni tradisi tidak pernah netral. Ia berpihak pada keselamatan bersama. Ia berdiri di antara manusia dan alam sebagai juru bicara yang setia. Maka, setiap kali bencana datang dan kita bertanya mengapa, barangkali jawabannya sudah lama didendangkan—hanya saja kita tidak lagi mendengarkan.
Di masa depan, mungkin ceh didong akan kembali mendendangkan bencana. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena kita kembali lalai. Dan jika itu terjadi, semoga kali ini nyanyian itu tidak hanya menjadi kenangan, melainkan peringatan yang sungguh-sungguh kita pahami.