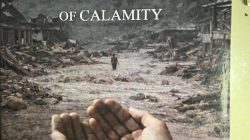Banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 26 November 2025 bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan keras —bahkan dakwaan terbuka—atas cara kita memperlakukan hutan, ruang hidup, dan masa depan sendiri. Rusaknya vegetasi hutan di hulu akibat penebangan, pembukaan lahan, dan pembiaran telah menjelma menjadi air bah yang menyeret rumah, ladang, dan harapan warga.
Pertanyaannya kini sederhana tapi menentukan: setelah bencana, mau apa?
Tiga Fase, Tapi Satu Arah atau Jalan di Tempat
Secara administratif, Aceh Tengah akan memasuki tiga fase pascabencana.
Pertama, tanggap darurat—fase yang menguras emosi dan logistik, tempat negara hadir dengan selimut, dapur umum, dan tenda.
Kedua, fase transisi selama sekitar 90 hari, yang seharusnya menjadi jembatan antara kepanikan dan perencanaan.
Ketiga, rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) yang diproyeksikan berlangsung tiga tahun.
Dan setelah itu, pemulihan lanjutan melalui RPJM Recovery, yang bisa memakan waktu 5 hingga 10 tahun.
Namun pertanyaannya bukan soal lamanya waktu. Pertanyaannya: apakah arah pemulihan ini jelas, atau sekadar rutinitas birokrasi yang berulang dari satu bencana ke bencana lain?
RPJM Recovery: Dokumen Hidup atau Arsip Mati
Dalam konteks kebencanaan, RPJM Recovery—atau dokumen sejenis seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) —bukan sekadar kertas berstempel. Ia adalah peta jalan yang menentukan apakah pemulihan akan berujung pada ketangguhan, atau justru melanggengkan kerentanan.
Dokumen ini seharusnya mengubah respons darurat menjadi pembangunan berkelanjutan pascabencana, bukan sekadar membangun kembali apa yang hancur di tempat yang sama, dengan risiko yang sama.
Peran Kunci Perencanaan Pemulihan: Lebih dari Sekadar Formalitas
Pertama, pedoman strategis terintegrasi.
Perencanaan pemulihan harus menjadi acuan bersama semua pemangku kepentingan—pemerintah daerah, provinsi, pusat, hingga lembaga non-pemerintah. Program pemulihan wajib terintegrasi dengan RPJMD, agar pemulihan tidak berjalan liar dan terlepas dari visi pembangunan daerah. Tanpa integrasi ini, yang lahir hanyalah proyek tambal-sulam.
Kedua, percepatan pemulihan ekonomi dan sosial.
Bencana bukan hanya merobohkan rumah, tapi juga memutus mata pencaharian. Pemulihan harus memprioritaskan infrastruktur vital, pemulihan usaha rakyat, pertanian, dan layanan sosial. Jika tidak, warga hanya dipindahkan dari satu bentuk kemiskinan ke bentuk kemiskinan lain—lebih rapi di atas kertas, tapi sama rapuh di lapangan.
Ketiga, membangun kembali dengan lebih baik (Build Back Better).
Rekonstruksi bukan nostalgia. Ini momentum untuk memperbaiki tata ruang, menghentikan praktik pembangunan yang merusak, dan menerapkan standar tahan bencana. Jika rumah dibangun kembali di jalur banjir, jika hutan tetap dibuka di hulu, maka yang dibangun sebenarnya hanyalah bencana berikutnya.
Keempat, transparansi dan akuntabilitas.
Dana pemulihan selalu besar—dan karena itu rawan. Target harus jelas, penanggung jawab harus nyata, dan mekanisme pelaporan harus terbuka. Tanpa itu, bencana akan menjadi ladang baru: bukan untuk ketahanan, tapi untuk kepentingan segelintir orang.
Mau Pulih, atau Sekadar Bertahan
Aceh Tengah dan Bener Meriah kini berada di persimpangan sejarah.
Apakah pemulihan akan menjadi jalan menuju daerah yang lebih tangguh, atau hanya siklus berulang antara rusak–dibangun–rusak lagi?
Bencana 26 November 2025 telah memberi jawabannya dengan cara paling brutal.
Sekarang giliran pemerintah dan masyarakat menjawab dengan keberanian politik, ketegasan kebijakan, dan perubahan cara pandang.
Karena jika setelah bencana kita hanya sibuk menata dokumen tanpa menata arah, maka pertanyaan “mau apa?” akan dijawab alam—dengan bencana berikutnya.